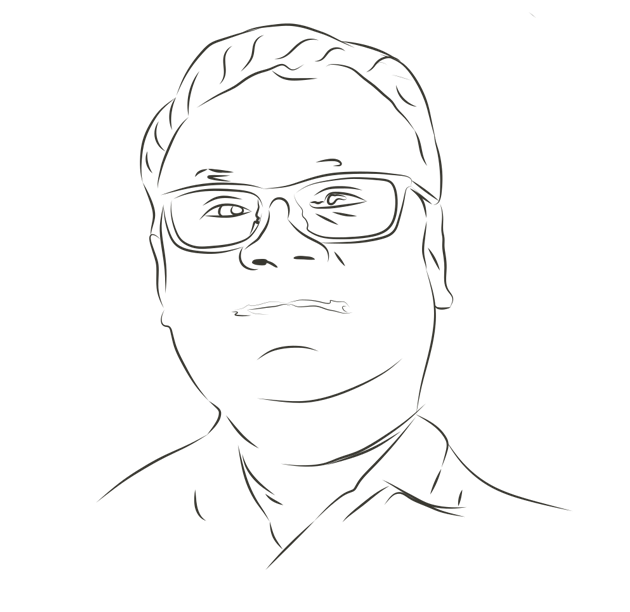Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Pepatah ini tepat untuk menggambarkan nasib seorang remaja perempuan berusia 15 tahun di Jambi berinisial WA. Dia divonis penjara selama 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian pada 19 Juli 2018 karena melakukan aborsi. WA melakukan aborsi karena ia hamil akibat diperkosa oleh kakak kandungnya sendiri.
Secara umum, praktik memang dilarang oleh hukum. Meski demikian, berdasarkan Pasal 75 (2) UU Kesehatan Nomor 36 tahun 2009, ada pengecualian dengan kondisi tertentu. Tindakan aborsi diizinkan jika ada indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan yaitu jika:
- Mengancam nyawa ibu dan/atau janin,
- Kehamilan itu akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
Pada pasal berikutnya, aborsi hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat ini:
- Usia kehamilan kurang dari enam minggu
- Mendapat persetujuan dari wanita yang hamil itu
- Dilakukan oleh lembaga medis bersertifikat yang ditunjuk oleh negara.
Persoalannya, remaja yang lugu seperti WA ini belum tentu mengetahui informasi soal ini. Barangkali juga dia tidak bisa mengakses lembaga medis bersertifikat yang dimaksud dalam undang-undang itu. Sehingga yang bisa dilakukannya adalah melakukan aborsi secara ilegal. Tentu saja risikonya sangat besar. Pertama, risiko terbesar adalah menyangkut nyawa karena tanpa prosedur medis yang benar, maka tidak hanya janin yang meninggal, sang ibunya juga bisa ikut tewas. Kedua, risiko hukum seperti vonis yang telah diterima oleh WA.
Di sini kita patut prihatin karena sistem hukum kita belum memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual. Fokus utama peradilan hanya tertuju untuk menghukum kepada pelaku, namun tidak mengindahkan bagaimana cara memulihkan korban perkosaan.
Patriarkhi
Fenomena aborsi karena kehamilan yang tidak dikehendaki seperti puncak dari gunung es. Peristiwa-peristiwa yang terungkap hanya sebagian kecil. Pada kenyataannya, ada lebih banyak lagi praktik aborsi yang tidak pernah diungkapkan ke publik. Selain karena perkosaan, kehamilan yang tidak dikehendaki itu terjadi karena akibat hubungan seks di luar pernikahan. Karena sebab apa pun, pihak perempuan berada dalam posisi yang rentan. Selain risiko nyawa, pihak perempuan juga akan menyandang stigma atau stempel buruk dari masyarakat.
Inilah gambaran relasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Akar penyebabnya adalah dari budaya patriarkhi yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang lebih unggul daripada perempuan. Laki-laki ditempatkan lebih berkuasa sehingga merasa punya hak untuk mengatur kehidupan perempuan. Dalam perspektif ini, tindakan perkosaan terjadi karena pihak laki-laki merasa lebih berkuasa sehingga memaksakan kehendaknya pada perempuan. Dia memandang perempuan sebagai properti yang dapat diperlakukan sekehendak nafsunya.
Kemudian ketika kehamilan terjadi, maka pihak perempuan lebih banyak menanggung malu. Alih-alih mendapat empati, kadangkala masyarakat justru menyalahkan sang korban, yaitu perempuan, sebagai penyebab dari perkosaan itu. “Apakah kamu memakai pakaian seksi?”, “Kamu sih sok kegenitan!”, “Saat itu kamu jalan sendiri ya.” Seperti itulah kata-kata penghakiman yang dihujamkan pada perempuan yang sudah terluka.
Peran Agama
Aborsi kadang menjadi pilihan bagi perempuan yang hamil karena diperkosa. Meski demikian, dalam sudut pandang agama, pengguguran kandungan ini dipandang sebagai perbuatan terlarang. Aborsi ini menjadi persoalan dilematis dan pelik sampai sekarang. Di satu sisi, ada banyak perempuan yang tewas akibat tindakan aborsi tidak aman karena ilegal. Tapi di sini lain, secara moral dan agama, aborsi dipandang sebagai tindakan pembunuhan.
Mau tak mau, lembaga agama memang harus bersikap tegas dengan menolak aborsi. Meski demikian, terhadap perempuan yang mengalami kehamilan-tak-dikehendaki, lembaga agama hendaknya bersikap bijak. Terhadap perempuan yang hamil karena korban tindakan kekerasan seksual, lembaga agama hendaknya bersikap welas asih. Tindakan mengecam, justru akan membuat perempuan tersebut akan menjauh dari agama. Maka yang sebaiknya dilakukan adalah kaum agamawan merengkuh dan mendampingi korban selama kehamilan berlangsung tanpa menunjukkan sikap penghakiman. Seandainya, sang ibu nanti menolak membesarkan anak yang dikandungnya, maka lembaga agama tersebut dapat menawarkan bantuan untuk menampung anak tersebut. Dengan demikian tidak ada aborsi. Keuntungannya, sang ibu tidak akan menanggung perasaan bersalah (berdosa) karena telah menggugurkan kandungan.
Selain itu, pekerjaan rumah yang lebih besar adalah mengikis budaya patriarkhi. Tidak ada agama di dunia ini yang mengajarkan penindasan manusia terhadap sesamanya. Semua agama mengajarkan bahwa manusia itu setara di hadapan Tuhan, apa pun jenis kelaminnya. Memang untuk mengubah tata-nilai itu tidak semudah membalik telapak tangan karena sudah terlanjur mengurat akar dalam masyarakat. Hal ini dibutuhkan kerja keras dan konsistensi dalam waktu yang lama.